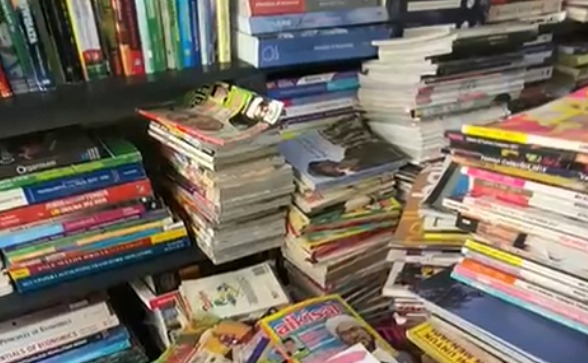Edisi/elshinta.com
● Harmoni antara komunitas Tionghoa dan masyarakat lokal mulai terbangun melalui interaksi sehari-hari.
● Negosiasi budaya terjadi baik di ruang privat seperti perkawinan beda etnis, maupun ruang publik seperti persahabatan antaretnis.
● Solidaritas lintas etnis bisa tumbuh kuat melalui hubungan pribadi dan saling membantu.
EDISI.CO, CATATAN EDISIAN– Mei 1998 barangkali menyimpan memori kolektif yang sama bagi masyarakat Indonesia: Kota-kota seperti Jakarta dan Solo mengalami ketegangan, toko-toko dijarah, perempuan-perempuan mengalami kekerasan, penganiayaan, bahkan pemerkosaan.
Memori tersebut telah memperkuat stereotip antaretnis.
Sebelumnya, komunitas Tionghoa sudah kerap diasosiasikan dengan komunisme yang ada di Cina, dan karenanya mudah menjadi sasaran penganiayaan dalam perubahan rezim politik.
Sebaliknya, masyarakat Tionghoa juga memiliki stereotip negatif tentang masyarakat lokal. Dalam interaksi saya bersama dengan sebuah keluarga Tionghoa di Solo, mereka memperkenalkan istilah: huana ren untuk menyebut pribumi. Artinya, seseorang yang asing, bukan merupakan bagian dari komunitas Tionghoa.
Kini, 27 tahun setelah Reformasi 1998, penelitian saya menunjukkan adanya kabar baik, yaitu menguatnya harmoni antaretnis di berbagai aspek kehidupan komunitas Tionghoa dan masyarakat lain.
Berbagi ruang hidup
Akibat stereotip yang ada di masyarakat, komunitas Tionghoa cenderung berpisah ruang hidup dengan masyarakat lain. Pribumi tinggal di pemukiman perkampungan, sedangkan komunitas Tionghoa di perumahan satu pintu (gated community).
Pribumi belajar di sekolah negeri, sedangkan komunitas Tionghoa di sekolah swasta. Pribumi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, sedangkan komunitas Tionghoa menjadi pedagang dan pemilik toko di jalan utama kota.
Pemisahan ini mengakar sedemikian kuat dan memberi pesan bahwa kedua golongan ini berbeda, tidak dapat disatukan, sehingga rentan mengalami ketegangan.
Namun, terdapat beberapa situasi yang memungkinkan harmoni tetap muncul, baik di ruang privat seperti pernikahan maupun ruang publik seperti warung makan.
1. Perkawinan Jawa dan Tionghoa
Riset saya pada tahun 2020 meneliti 10 pasangan Jawa dan Tionghoa di Jawa Timur. Pada penelitian ini, saya mengeksplorasi bagaimana dua orang yang berasal dari dua etnis yang berbeda membangun hidup bersama. Selama 10 minggu, saya melakukan wawancara dan turut terlibat dalam kegiatan mereka sehari-hari (go-alongs).
Pasangan-pasangan ini menunjukkan bagaimana mereka mengatur kehidupan rumah tangga dan relasi dengan keluarga besar serta masyarakat sekitarnya. Termasuk di dalamnya menavigasikan stereotip negatif yang ada di dalam masing-masing etnisnya.
Hasil penelitian saya menunjukkan bahwa meskipun ketegangan yang disebabkan karena perbedaan etnis tetap muncul, para partisipan selalu berusaha untuk mencari jalan tengah agar rumah tangganya tetap berjalan.
Nilai-nilai dan praktik yang berbeda dinegosiasikan, dan mereka menciptakan praktik sosial yang baru, sebagai ruang ketiga (the third space), untuk mengakomodasi semua kepentingan.
“Aku pernah datang ke rumah Ayah mertuaku yang merupakan Tionghoa, dan beliau mengatakan bahwa lipstikku merah, seperti perempuan murahan. Aku sangat marah sekali. Dari kecil, ibuku yang adalah seorang Raden Roro mengajarkanku kalau yang namanya lipstik itu ya harus merah tajam. Itulah sang istri utama. Warna nude itu untuk selir. Aku marah sekali (pada ayah mertua) dan tidak mengunjunginya selama 3 minggu. Tapi kan mengunjungi mertua adalah kewajiban anak. Jadi aku menyediakan lipstik berbagai warna di mobil, beserta tisu. Aku hapus lipstik merahku dan menggantinya menjadi warna nude kalau suamiku mengajak ke rumah ayah mertuaku tiba-tiba”._
Riset saya tersebut juga menunjukkan upaya keluarga untuk membangun harmoni melalui hal-hal sederhana seperti makanan. Suami Tionghoa yang umumnya menikmati makanan khas seperti Bak Kut Teh setiap malam tahun baru (Sincia), tidak lagi menikmatinya ketika menikah dengan istrinya yang beretnis Jawa.
Baca juga: Warga Rempang Datangi BP Batam, Sampaikan Keberatan soal Penggusuran
Tetapi sang istri, dengan pengalaman dan latar belakang memasak dari keluarga Jawa, belajar memasak menu tersebut dengan kombinasi resep ibu mertua dan pengalaman dari keluarganya sendiri, sehingga menghasilkan masakan dengan rasa yang baru.
“Aku tahu suamiku kerap makan bersama menyantap masakan ibunya di malam Sincia. Setelah kami menikah dan ibunya meninggal, tradisi itu tidak lagi ada. Tapi aku mau setelah kami menikah, dia tetap menikmati masakan itu. Aku belajar sendiri memasak Bak Kut Teh. Kucampur sedikit dengan bumbu kecap dan ketumbar, seperti biasanya orang Jawa mengolah daging. Dia bilang rasanya berbeda (dengan masakan ibunya). Kutanya, “Enak?”. “Sama-sama enak”, katanya (tertawa)“.
Contoh di atas menunjukkan bahwa meskipun ketegangan antaretnis ini ada, para pasangan berupaya untuk mencari cara agar rumah tangga mereka tetap harmonis. Kasih sayang kepada pasangan dan rasa hormat kepada orangtua masing-masing menjadi salah satu sumber energi untuk memastikan bahwa rumah tangga mereka tetap dapat berjalan dengan baik.
2. Persahabatan pedagang pecel dan pemilik ruko
Harmoni antaretnis tidak hanya terjadi di ruang privat, tetapi juga di ruang publik. Pada tahun 2023, saya melakukan riset terhadap penjual nasi pecel di Madiun, Kediri, Nganjuk, dan Jombang, di Jawa Timur, dan menemukan sebuah pola yang sama: Semua nasi pecel malam yang dijual berderet di jalan utama pusat kota, dijual oleh para pedagang pecel lokal dan mengambil lokasi di depan ruko yang dimiliki oleh pengusaha Tionghoa.
Saya dan tim menelusuri jalan-jalan tersebut untuk berinteraksi dengan para pedagang dan mendapatkan testimoni mengenai persahabatan mereka dengan para pemilik toko yang telah berlangsung berpuluh-puluh tahun—bahkan hingga lintas generasi.
“Setiap hari, aku datang 30 menit lebih awal untuk nyapa si engkoh, menyapa saja. Kabarnya bagaimana? Keluarganya bagaimana? Aku itu berdagang di sini untuk bertahan hidup, wong keuangan terbatas. Tapi kok ya si engkoh ngasih aku tempat jualan di sini gratis. Dari dulu, ibuku jualan, sampai diwariskan ke aku. Aku sering undang dia makan nasi pecel di sini. Sambil ngobrol. Itu caraku berterima kasih”.
Riset saya menemukan bahwa persahabatan antaretnis inilah yang memungkinkan para pedagang pecel menempati lokasi yang sama secara gratis.
Jika pun ada biaya, sangatlah murah, dan dibayarkan melalui paguyuban. Mereka dapat menempati lokasi-lokasi ini, lengkap dengan akses terhadap air dan listrik, hanya bermodal pesan dari pemilik toko untuk tetap menjaga kebersihannya.
“Engkoh memperkenalkan aku sama Pak RT yang membantu mengatur kabel supaya ada lampu. Gratis. Tapi ada iuran sedikit ke paguyuban. Nah, terus ada tetangga lagi yang ngasih air untuk cuci piring. Aku kalau nggak ada mereka ya nggak bisa jualan. Aku mau membayar saja, mereka tidak mau. Wah, terbaik. Orang ngomong Cina itu begini, begitu. Bagiku enggak. Mereka sudah membantuku mencari penghidupan”.
Pemahaman kita mengenai relasi Tionghoa dan non-Tionghoa selama ini didominasi oleh cerita yang bernuansa politik dan penuh ketegangan, seperti narasi pribumi dan nonpribumi.
Namun, riset-riset di atas menunjukkan bahwa di akar rumput, masih ada banyak pengalaman tentang harmoni antaretnis yang menghangatkan hati, yang layak untuk diceritakan dari generasi ke generasi.
Penulis: Jony Eko Yulianto, Community and Applied Social Psychologist, Universitas Ciputra
Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.