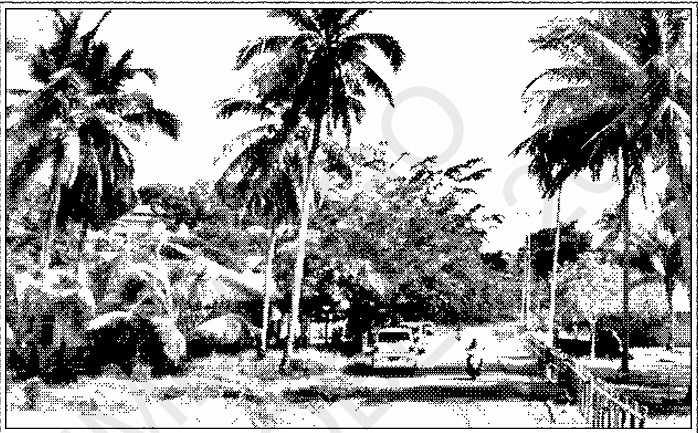EBT Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Dok; Ist.
EDISI.CO, CATATAN EDISIAN– Upaya pemerintah untuk menggenjot transisi energi terbarukan hingga saat ini masih berfokus pada pembangunan pembangkit listrik berskala besar. Mulai dari pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Batang Toru di Sumatra Utara, hingga proyek panas bumi di Wae Sano, Nusa Tenggara Timur.
Sayangnya, fokus ini justru menciptakan berbagai masalah sosial dan lahan. Belum lagi risikonya terhadap keberagaman hayati.
Proyek listrik berskala besar juga tak menjamin akses listrik yang merata terutama bagi penduduk di desa-desa terpencil. Per akhir 2022, saat Indonesia tengah surplus listrik tercatat ada 4.400 desa yang belum teraliri setrum.
Untuk mencapai transisi energi yang berkeadilan—terutama bagi warga pelosok, pemerintah perlu pendekatan baru untuk memprioritaskan penyediaan energi terbarukan berbasiskan sumber daya lokal dan dikelola masyarakat. Ketergantungan pemerintah terhadap perencanaan ala PLN perlu dikurangi. Sebaliknya, upaya masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan energinya secara mandiri nan lestari, perlu didukung habis-habisan.
Riset kami bersama organisasi pegiat isu lingkungan, 350.org, mencoba menelaah manfaat pemerintah apabila menggunakan pendekatan energi berbasis komunitas sebagai langkah prioritas transisi energi. Kami menghitung, dalam 25 tahun ke depan, energi terbarukan berbasis komunitas justru menghasilkan dampak ekonomi hingga Rp18.636 triliun dan mengangkat 16 juta penduduk dari kemiskinan.
Menggeliatkan sektor usaha dan meratakan pertumbuhan
Kami melakukan simulasi pengembangan energi terbarukan berbasis komunitas berdasarkan pertumbuhan tahunan rata-rata energi surya (PLTS) dan mikrohidro (PLTM) selama lima tahun terakhir. Kedua energi ini acap digunakan dalam proyek energi terbarukan berbasis komunitas di Indonesia.
Kami juga memasukkan sumber energi terbarukan lainnya, seperti angin (PLTB), yang potensial digunakan dalam proyek energi skala kecil.
Dari pertumbuhan energi tersebut, kami menghitung dampaknya ke masyarakat dan berbagai sektor perekonomian di sekitarnya dengan pemodelan Interregional Input-Output (IRIO). Studi kami juga menghitung dampaknya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja.
Hasilnya, pertumbuhan energi terbarukan berbasis komunitas selama 25 tahun dapat menghasilkan output ekonomi rata-rata sebesar Rp745 triliun per tahun. Nilai ini berasal dari nilai investasi energi terbarukan, penyerapan tenaga kerja untuk pemasangan dan perawatan. Hasil industri lokal seperti olahan perkebunan rakyat, pariwisata, kerajinan, dan industri rumah tangga lainnya juga akan meningkat karena masuknya listrik ke daerah mereka.
Beberapa daerah, seperti di Lumajang; Jawa Timur, juga menunjukkan hubungan positif antara energi berbasis komunitas dengan praktik ekonomi restoratif (yang memulihkan alam serta masyarakat). Sebab, air untuk PLTM juga digunakan untuk mengairi perkebunan yang berkelanjutan. https://www.youtube.com/embed/YE_ir0almTQ?wmode=transparent&start=0 PLTMH Gunung Sawur, penghasil listrik berbasis komunitas yang berhasil mengungkit kesejahteraan warga.
Energi terbarukan berbasis komunitas juga dapat berkontribusi pada PDB sebesar Rp10.463 triliun secara kumulatif dalam 25 tahun ke depan. Kontribusi terbesar pada tahun ke-25 akan berasal dari sektor pengolahan (Rp415 triliun), sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang konstruksi (Rp335 triliun, dan sektor pengadaan listrik, air, dan gas (Rp258 triliun).
Patut dicatat bahwa PDB ini akan bertumbuh nyaris merata—lebih tinggi di wilayah Indonesia timur (seperti Gorontalo, Maluku, Papua). Sebab, energi terbarukan berbasis komunitas akan menjadi suplai listrik murah dan stabil menggantikan suplai energi konvensional yang belum ada dan sukar tersedia sepanjang hari. Energi yang stabil akan meningkatkan produktivitas masyarakat, badan usaha desa dan koperasi, serta usaha-usaha kecil setempat.
Merangsang green jobs dari desa
Ekonomi desa yang menggeliat juga akan menciptakan lapangan kerja dari pinggiran. Studi kami menaksir, selama 25 tahun, ribuan proyek energi terbarukan berbasis komunitas dapat menyerap 96 juta lebih pekerja. Serapan tertinggi berada di sektor green jobs seperti bidang manufaktur dan distribusi peralatan energi terbarukan, pengembangan proyek, konstruksi dan pemasangan, operasi dan pemeliharaan, dan bidang lintas sektor yang umum.
Baca juga: Akar Kekerasan Infrastruktur yang Menjerumuskan “Orang Laut” Menjadi Pemulung
Lagi-lagi, dengan model energi terbarukan yang terdesentralisasi, penciptaan lapangan kerja juga berpeluang terjadi secara merata. Pada tahun ke-25, misalnya, pemodelan kami menaksir penyerapan kerja tinggi di provinsi seperti Kalimantan Timur (1,39 juta pekerja), Nusa Tenggara Timur (1,7 juta), dan Nusa Tenggara Barat (1,3 juta).
Selain banyak penyerapan, studi kami juga meramalkan total pendapatan pekerja nasional meningkat hingga Rp510,9 triliun pada tahun ke-25. Kenaikan penyerapan pekerja juga merangsang peluang beraneka green jobs dengan keahlian khusus bidang energi terbarukan. Potensi ini perlu dijawab dengan pelatihan vokasi maupun penguatan Balai Latihan Kerja (BLK) di daerah-daerah.
Dari mana uangnya?
Melistriki ribuan desa bukan pekerjaan mudah. Jika berniat memprioritaskan energi terbarukan berbasis komunitas, pemerintah perlu menyiapkan kebijakan untuk membuka peluang sumber pendanaan.
Kami mencoba mengidentifikasi sumber-sumber mana saja yang potensial untuk mendanai proyek energi terbarukan berbasis komunitas, di antaranya:
1. Anggaran negara
Indonesia dapat memanfaatkan anggaran negara yang sudah ada seperti Dana Desa untuk mendanai energi terbarukan berbasis komunitas. Kita juga bisa menerapkan kebijakan baru seperti menggeser anggaran subsidi energi fosil, dana bagi hasil sumber daya alam di masing-masing daerah, dan realokasi insentif fiskal dari yang selama ini diterapkan bagi industri batu bara ke proyek energi terbarukan.
Pemerintah juga dapat merumuskan kebijakan progresif yang menguntungkan pendanaan energi terbarukan berbasis komunitas. Beberapa di antaranya adalah pajak windfall profit (keuntungan dari lonjakan harga komoditas), pajak kekayaan, pajak produksi batu bara, pajak karbon, ataupun pembentukan dana abadi untuk pengembangan energi terbarukan.
2. Anggaran internasional
Indonesia melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP) mendapatkan komitmen pendanaan dari negara-negara maju sebesar US$20 miliar (Rp320 triliun). Sayangnya, rencana investasi JETP masih berfokus pada energi terbarukan berskala besar. Pendanaan pun dominan menggunakan mekanisme utang, bukan hibah.
Pemerintah semestinya bisa melakukan renegosiasi kepada negara maju untuk memberikan hibah. Bisa pula renegosiasi berfokus agar negara maju mengalihkan piutangnya (debt swap) di Indonesia ke proyek transisi energi terbarukan berbasis komunitas.
Skema ini berguna menekankan aspek keadilan sosial dalam JETP.
3. Perbankan dan pasar modal
Indonesia perlu menyiapkan kebijakan yang merangsang perbankan dan lembaga modal ventura untuk lebih banyak membiayai proyek energi terbarukan berbasis komunitas. Pembiayaan juga dapat digenjot melalui koperasi ataupun penerbitan instrumen keuangan (seperti sukuk, reksadana) yang menghimpun dana masyarakat untuk membiayai proyek-proyek energi bersih.
Persiapan
Upaya menggeser paradigma transisi energi pemerintah dari proyek berskala besar ke skala komunitas memang tidak mudah. Ini membutuhkan komitmen politik untuk melaksanakan transisi energi yang berkeadilan dalam jangka panjang.
Selain itu, banyak juga aspek teknis yang perlu dipikirkan seperti perencanaan proyek, pemeliharaan pembangkit listrik oleh warga, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban dana. Gagasan ini membutuhkan pemikiran dan partisipasi bersama dari seluruh pemangku kepentingan, terutama warga desa yang siap bahu-membahu menyiapkan listrik energi terbarukan di kampung masing-masing.
Penulis: Bhima Yudhistira Adhinegara, Direktur, Center of Economic and Law Studies (CELIOS)
Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.